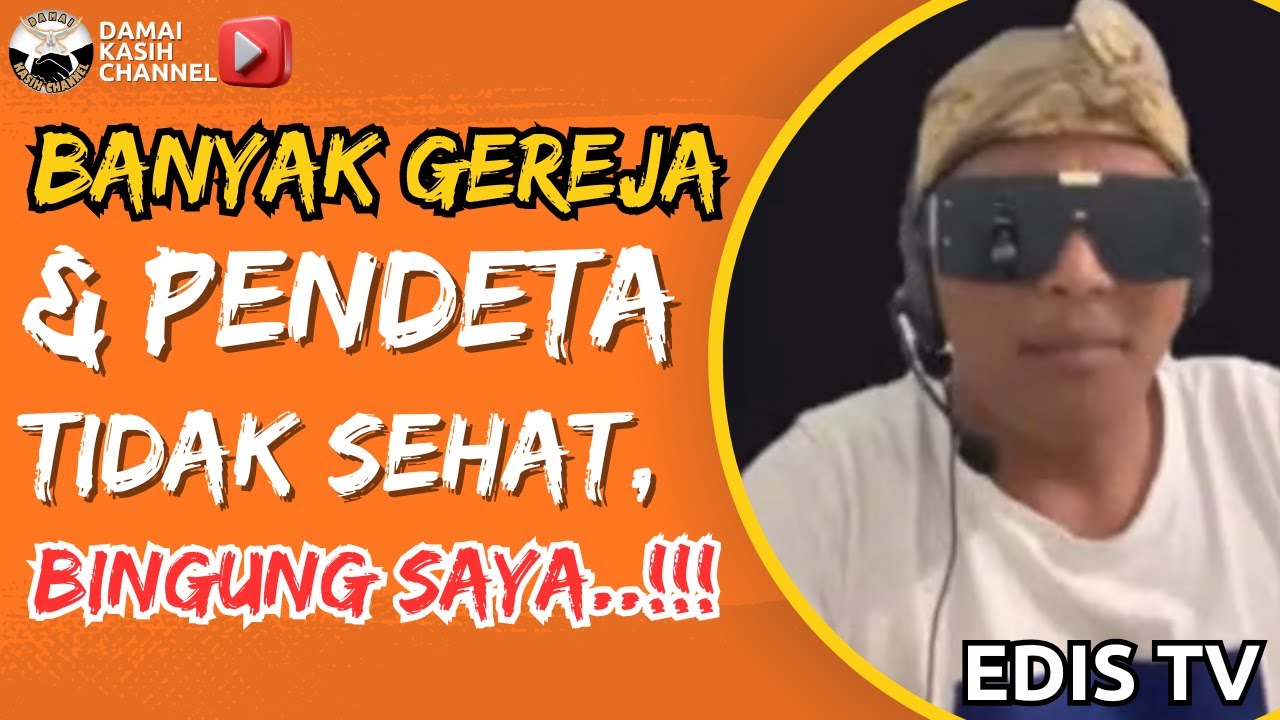LIVE DKC [83-2025] JUMAT, 4 JULI 2025 PUKUL 19:00 WIB: MEWARTA KOK FRAMING KATOLIK!!! APA YG KAMU WARTAKAN??? @EDISTV
Merespon Video EDISTV ”Iconoclasm adalah Ajaran yang Sudah Dianatema Gereja pada Abad 8, Adanya Ikonoclasm Dipengaruhi Kemunculan Islam”
THE SACRAMENTARIANS
Bapak dari para Sakramentarian adalah Andrew Carlostad yang juga pengikut Luther pada mulanya, Dia lahir di desa yang dia ambil sebagai namanya, di Franconia, Dia merupakan eks Diakon Agung dari gereja Wittemberg. Dia dikatakan sebagai orang yang paling terpelajar di Saxony, dan oleh karena itu, dia sangat disukai oleh para pengikut Frederick. Dialah yang mengakui Luther sebagai Doktor, dan setelah itu menjadi pengikut bid’ahnya. Akan tetapi, harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk tetap menjadi murid Luther, dan dengan demikian dia menjadi kepala Sakramentarian, mengajar dan menentang Luther, bahwa Kristus tidak benar-benar hadir dalam Ekaristi, dan oleh karena itu, kata ini (ini tubuhku) tidak mengacu pada roti, tetapi untuk Kristus sendiri, yang akan mengorbankan tubuhnya bagi kita, seolah-olah dia berkata: “Inilah tubuhku yang ada di sekitarku untuk diserahkan untukmu”.
Kesalahan lain yang dia ajarkan bertentangan dengan Luther, adalah doktrin Ikonoklas, bahwa semua salib dan gambar orang suci harus dihancurkan. Dia menghapus Misa, menginjak-injak Hosti yg telah dikonsekrasi & menghancurkan altar dan gambar orang kudus.1
Menghapus Wajah Tuhan: Kegagalan Perang Melawan Ikon
Ikonoklasme adalah konflik teologis, politik, dan budaya yang mengguncang Kekaisaran Bizantium, terutama di Konstantinopel, antara abad ke-8 dan ke-9, dengan dampak yang bergema hingga masa Kesultanan Ottoman dan Reformasi Protestan. Krisis ini (726 - 843), dipicu Kaisar Leo III dan diperparah Konsili Hieria (754), memanfaatkan sikap anikonik Islam dan Yudaisme untuk menghancurkan ikon-ikon suci. Konsili Nicea II (787) membalikkan kebodohan ini, menegaskan ikon sebagai cermin Inkarnasi Kristus.
Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman pada 1453, warisan ikonoklasme terlihat dalam perubahan fungsi Hagia Sophia. Di Barat, Andreas Bodenstein von Karlstadt (Carlstat) menghidupkan kembali semangat serupa selama Reformasi, namun gagal melawan otoritas teologis Nicea II.
Artikel ini menganalisis ikonoklasme di Konstantinopel, Konsili Hieria, pengaruh Islam dan Yudaisme, dampak Ottoman, kegagalan Carlstat, dan kemenangan Nicea II, dengan mempertimbangkan aspek teologis, historis, politik, budaya, dan lintas agama, merujuk pada sumber otoritatif dan dokumen resmi Gereja Katolik.
Ikonoklasme di Konstantinopel: Ambisi Kekaisaran Melawan Iman
Ikonoklasme Bizantium (726 - 787, 814 - 842) dimulai pada 726 ketika Kaisar Leo III memerintahkan penghancuran ikon Kristus di gerbang Chalke Konstantinopel, mengatasnamakan Keluaran 20:4 – ”Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun” – dan mencap ikon sebagai penyembahan berhala. “Kaisar ingin membatasi kultus ikon yang semakin meluas,” tulis Encyclopedia of World History (2001). Tindakan ini lebih merupakan strategi politik untuk menekan biarawan ikonodul, yang memiliki pengaruh spiritual besar, dan menangkal ancaman militer Umayyah, dengan meminjam retorika anikonik Islam dan Yudaisme. Leo III memicu perpecahan berdarah, dengan resistensi dari masyarakat awam dan biara yang menyembunyikan ikon (The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Hussey, 2010).
Konstantinus V memperhebat krisis melalui Konsili Hieria, menjadikan ikonoklasme kebijakan resmi. “Biarawan disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh,” catat History of the Eastern Church (1998). Gereja-gereja Konstantinopel kehilangan mozaik dan ikon, digantikan ornamen non-figural. Faksi militer dan elit istana mendukung kaisar, melihat ikonoklasme sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan (Byzantium in the Iconoclast Era, Brubaker & Haldon, 2011). Krisis mereda di bawah Ratu Irene melalui Konsili Nicea II (787), namun kembali muncul pada 814 hingga Theodora mengakhirinya pada 842 dengan “Triumph of Orthodoxy,” menandai kemenangan ikonodul.
Konsili Hieria: Politik Kekaisaran dalam Jubah Teologi
Konsili Hieria (754), diadakan di istana Hieria dekat Konstantinopel, adalah upaya Konstantinus V untuk melegitimasi ikonoklasme. Dengan 338 uskup yang tunduk pada kaisar, konsili ini menyatakan bahwa ikon adalah penghujatan: “Gambar Kristus tidak dapat menangkap keilahian-Nya” (History of the Eastern Church, 1998). Mereka mempromosikan salib dan Ekaristi sebagai simbol sah, menolak ikon sebagai “seni haram yang menghujat Inkarnasi” (Byzantium in the Iconoclast Era, 2011).
Hieria tidak memiliki legitimasi ekumenis karena absennya perwakilan dari Roma dan patriarkat lain seperti Alexandria, Antiokhia, atau Yerusalem. “Hieria hanyalah alat kaisar, bukan konsensus Gereja,” tulis Encyclopedia of the History of the Church (2001). Penganiayaan terhadap ikonodul, termasuk martir St. Theodosia, yang menentang penghancuran ikon di Chalke, memperdalam perpecahan hingga Nicea II membatalkan keputusan Hieria.
Pengaruh Islam dan Yudaisme: Dalih untuk Kontrol Kekaisaran
Pengaruh Islam terlihat dari tradisi anikoniknya, berpijak pada Hadis: “Pembuat gambar akan diminta menghidupkannya pada Hari Penghakiman, namun gagal” (Sahih Muslim, 818 - 875). Edict of Yazid II (722 - 723), yang melarang gambar figural di wilayah Umayyah, memengaruhi polemik anti-ikon, sebagaimana dicatat History of the Patriarchs of Alexandria (ed. Evetts, 1904). “Kontak dengan Islam mungkin memengaruhi Leo III,” tulis Byzantium and Islam: Age of Transition (2012). Persaingan visual terlihat dari koin Justinian II bergambar Kristus (692), yang memicu respons anikonik Khalifah Abd al-Malik (697 - 698) (A Companion to Byzantine Iconoclasm, 2021). Komunitas Kristen di wilayah Umayyah, seperti di Yordania, menyesuaikan mozaik mereka dengan sensitivitas anikonik Islam (Islam and Image, Flood, 2019). Namun, “tidak ada bukti langsung bahwa Islam menjadi penyebab utama ikonoklasme” (Byzantium in the Iconoclast Era, 2011).
Yudaisme memberikan pengaruh melalui penafsiran ketat Keluaran 20:4. “Komunitas Yahudi di Bizantium menolak gambar figural, memengaruhi polemik Kristen,” tulis The Image Debate (Parry, 2017). Disputatio adversus Judaeos karya Leontios dari Neapolis menunjukkan bahwa ikonoklas meminjam argumen Yahudi, mencap ikon sebagai pelanggaran Taurat. “Pengaruh Yudaisme terbatas karena komunitas Yahudi lemah secara politik,” catat Parry (2017). “Ikonoklasme lebih tentang kekuasaan kaisar daripada teologi,” tegas The Oxford Handbook of Byzantine Studies (2008). Islam dan Yudaisme menjadi alat retoris bagi Leo III dan Konstantinus V untuk mengendalikan Gereja dan masyarakat.
Konsili Nicea II: Pembelaan Teologis terhadap Ikon
Konsili Nicea II (24 September - 23 Oktober 787), di bawah Ratu Irene dan Patriark Tarasius, adalah respons teologis yang kuat terhadap ikonoklasme. Dihadiri 350 uskup, termasuk legatus Paus Hadrianus I, konsili ini menegaskan ikon sebagai cermin Inkarnasi, membangun argumen teolog seperti Yohanes dari Damaskus, yang dalam On the Divine Images (1980) menyatakan: “Ikon bukanlah berhala, tetapi sarana untuk menghormati yang ilahi.” “Penghormatan terhadap ikon adalah bagian integral ibadah Kristen,” tulis Encyclopedia of the History of the Church (2001). Konsili membedakan latria (penyembahan untuk Allah) dari dulia (penghormatan untuk ikon): “Ikon-ikon suci diberi penghormatan, bukan penyembahan” (Acta Conciliorum Oecumenicorum, 1996). Denzinger-Hünermann: Enchiridion Symbolorum (2012) menegaskan: “Penghormatan terhadap ikon adalah pengakuan misteri Inkarnasi” (DH 600–603). Katekismus Gereja Katolik (1997) menambahkan: “Ikon suci menghormati pribadi yang digambarkan, tidak bertentangan dengan perintah pertama” (KGK 2132).
Konsili menolak argumen ikonoklas yang meminjam kekakuan Yahudi, menegaskan bahwa Inkarnasi – Allah yang menjadi manusia – mengubah penafsiran Perjanjian Lama. Hieria dicap “pseudo-sinode,” dan ikonoklasme dianatemakan: “Barang siapa menolak penghormatan terhadap ikon, anatema baginya” (Encyclopedia of the History of the Church, 2001). Konsili ini mengembalikan ikon ke Hagia Sophia dan gereja-gereja lain, memicu kebangkitan seni Bizantium pada abad ke-9, seperti mozaik baru di Hagia Sophia (The Oxford Handbook of Byzantine Studies, 2008). Nicea II juga memperkuat kesatuan Gereja Timur dan Barat, meskipun ketegangan tetap ada hingga Skisma 1054. Krisis ikonoklasme berakhir pada 842 di bawah Theodora dengan perayaan “Triumph of Orthodoxy.”
Pengaruh Ottoman: Hagia Sophia dan Redupnya Ikon
Pada 29 Mei 1453, Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, mengubahnya menjadi Istanbul. Hagia Sophia, pusat spiritual Kristen, menjadi masjid, dan mozaiknya ditutup dengan kapur, mencerminkan tradisi anikonik Islam yang pernah memengaruhi ikonoklasme Bizantium. “Pergantian kekuasaan memutus jalur perdagangan antara Eropa dan Asia,” tulis Sejarah Penaklukan Konstantinopel (Kompas, 2020).
Namun, mozaik tidak dihancurkan sepenuhnya, menunjukkan pendekatan pragmatis Ottoman untuk mempertahankan warisan budaya demi kepentingan politik. “Konstantinopel adalah jembatan antara Timur dan Barat,” catat Sejarah Konstantinopel (2005). Meskipun ikon meredup di Istanbul, warisan teologis Nicea II tetap hidup di Gereja Barat dan komunitas Ortodoks yang bertahan.
Carlstat: Ikonoklasme Reformasi yang Gagal
Selama Reformasi Protestan, Andreas Bodenstein von Karlstadt menghidupkan kembali semangat ikonoklasme dengan mencap gambar religius sebagai “jerat yang menyesatkan umat dari Kitab Suci” (De Canonicis Scripturis, 1520). Ia memicu kerusuhan di Wittenberg, menghancurkan ikon dan patung, tetapi pendekatannya ditolak oleh Martin Luther sebagai terlalu radikal. Berbeda dengan Hieria, yang didukung kekuatan kekaisaran, gerakan Carlstat tidak memiliki fondasi institusional dan gagal memengaruhi arus utama Reformasi.
Pandangan serupa dari reformator seperti Huldrych Zwingli dan Jean Calvin, yang juga menolak gambar tetapi dengan argumen lebih terstruktur, menunjukkan bahwa ikonoklasme Carlstat kurang koheren (Reformation and the Visual Arts, Christensen, 1992). Nicea II, dengan doktrin Inkarnasinya, mematahkan argumen Carlstat yang menggemakan kekakuan Yahudi terhadap larangan gambar.
Kontradiksi Ikonoklasme
Ikonoklasme, dari Hieria hingga Carlstat, mencerminkan kontradiksi antara ambisi duniawi dan iman Kristen. Konsili Hieria, meskipun mengklaim membela kemurnian agama, adalah alat politik Konstantinus V untuk mengendalikan Gereja dan biarawan ikonodul, didukung oleh faksi militer dan elit istana. Pengaruh Islam dan Yudaisme, meskipun nyata dalam retorika anikonik, hanya dimanfaatkan sebagai dalih untuk memperkuat otoritas kekaisaran. “Ikonoklasme lebih tentang kekuasaan kaisar daripada teologi,” tegas The Oxford Handbook of Byzantine Studies (2008). Konsili Nicea II, dengan argumen teologis yang berpijak pada Inkarnasi dan didukung oleh teolog seperti Yohanes dari Damaskus, membuktikan bahwa ikonoklasme tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan misteri Allah yang menjadi manusia (Denzinger-Hünermann, DH 600–603).
Penaklukan Ottoman atas Konstantinopel pada 1453 memperpanjang bayang-bayang ikonoklasme dengan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi ketahanan warisan Nicea II terlihat dalam kelangsungan tradisi ikon di Gereja Barat dan komunitas Ortodoks. Kebangkitan seni Bizantium pasca-842, seperti mozaik di Hagia
Sophia, menjadi bukti kemenangan ikonodul (The Oxford Handbook of Byzantine Studies, 2008). Carlstat, dengan pendekatannya yang impulsif, gagal karena tidak memiliki landasan teologis yang kokoh dan dukungan institusional, berbeda dengan Zwingli atau Calvin yang menawarkan kritik lebih sistematis terhadap gambar (Reformation and the Visual Arts, 1992). Katekismus Gereja Katolik (KGK 2132) menegaskan bahwa ikon adalah sarana untuk menghormati kehadiran ilahi, bukan berhala. Krisis ini menunjukkan bahwa upaya menghapus wajah Tuhan melalui ikon selalu gagal melawan kebenaran teologis bahwa Allah telah memilih untuk terlihat dalam Kristus.
Kesimpulan
Ikonoklasme di Konstantinopel, yang dipicu Leo III dan diperkuat Hieria, adalah upaya keliru untuk menghapus ikon dengan dalih teologi, padahal didorong oleh ambisi politik. Islam dan Yudaisme menjadi alat retoris untuk kontrol kekaisaran. Konsili Nicea II mematahkan kebodohan ini, menegaskan ikon sebagai cermin Tuhan yang nyata, sebagaimana ditegaskan Denzinger-Hünermann (DH 600 - 603) dan Katekismus Gereja Katolik (KGK 2132). Resistensi masyarakat awam dan biara memperkuat kemenangan ikonodul, yang terwujud dalam kebangkitan seni Bizantium pasca-842. Ottoman meredupkan ikon di Hagia Sophia, tetapi warisan Nicea II tetap hidup di Barat dan komunitas Ortodoks. Carlstat hanyalah pengulangan kegagalan Hieria, kalah oleh otoritas teologis Nicea II. Konstantinopel, kini Istanbul, menjadi saksi ketahanan iman Kristen bahwa Allah yang tak terlihat telah memilih untuk terlihat – dan tak ada kekuatan duniawi yang dapat menghapus wajah-Nya.2
Pengaruh Ikonoklasme dalam Protestantisme: Dari Carlstat hingga Masa Kini
Ikonoklasme, yang mengguncang Kekaisaran Bizantium pada abad ke-8 dan ke-9, meninggalkan jejak panjang dalam sejarah Kristen, termasuk dalam Protestantisme selama Reformasi dan hingga masa kini. Krisis ikonoklasme Bizantium (726 - 843), yang dipicu Kaisar Leo III dan diperparah Konsili Hieria (754), mencoba menghapus ikon dengan dalih teologi, namun ditolak oleh Konsili Nicea II (787), yang menegaskan ikon sebagai cermin Inkarnasi Kristus. Pada abad ke-16, Andreas Bodenstein von Karlstadt (Carlstat) menghidupkan kembali semangat ikonoklasme selama Reformasi Protestan, menentang gambar religius dengan argumen yang menggemakan kekakuan Yahudi terhadap Keluaran 20:4. Meskipun gagal menguasai arus utama Reformasi, gagasan ikonoklasme memengaruhi berbagai denominasi Protestan, membentuk sikap terhadap seni religius hingga hari ini.
Artikel ini menganalisis pengaruh ikonoklasme dalam Protestantisme, dari Carlstat hingga perkembangan kontemporer, dengan mempertimbangkan aspek teologis, historis, dan budaya, merujuk pada sumber otoritatif dan dokumen resmi.
Ikonoklasme Carlstat: Percikan Reformasi yang Padam
Selama Reformasi Protestan, Andreas Bodenstein von Karlstadt, seorang teolog Jerman, menghidupkan kembali semangat ikonoklasme dengan mencap gambar religius sebagai “jerat yang menyesatkan umat dari Kitab Suci” (De Canonicis Scripturis, 1520). Dalam kerusuhan di Wittenberg (1521 - 1522), Carlstat mendorong penghancuran ikon dan patung di gereja, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap larangan membuat gambar dalam Keluaran 20:4. Pendekatannya menggemakan argumen Konsili Hieria (754), yang menolak ikon sebagai “seni haram yang menghujat Inkarnasi” (Byzantium in the Iconoclast Era, Brubaker & Haldon, 2011). Namun, Carlstat tidak mendapat dukungan luas. Martin Luther, figur sentral Reformasi, menolak pendekatan radikal Carlstat, berargumen bahwa gambar religius dapat digunakan sebagai alat pengajaran selama tidak disembah (Against the Heavenly Prophets, Luther, 1525). “Carlstat mengulang argumen usang yang telah dipatahkan Nicea II,” tulis Reformation and the Visual Arts (Christensen, 1992).
Kegagalan Carlstat tidak hanya karena kurangnya dukungan institusional, tetapi juga karena argumen teologisnya lemah dibandingkan Konsili Nicea II, yang membedakan latria (penyembahan untuk Allah) dari dulia (penghormatan untuk ikon) (Denzinger-Hünermann: Enchiridion Symbolorum, 2012, DH 600 - 603). Katekismus Gereja Katolik (1997) menegaskan: “Ikon suci menghormati pribadi yang digambarkan, tidak bertentangan dengan perintah pertama” (KGK 2132). Luther, meskipun kritis terhadap penyembahan berlebihan, mempertahankan penggunaan gambar seperti salib dan lukisan alkitabiah, sehingga mengecilkan pengaruh Carlstat dalam Lutheranisme.
Pengaruh Ikonoklasme pada Reformator Lain
Ikonoklasme Carlstat, meskipun gagal, menemukan gema dalam pandangan reformator lain seperti Huldrych Zwingli dan Jean Calvin, yang mengembangkan sikap lebih terstruktur terhadap gambar religius. Zwingli, di Zurich, memimpin penghapusan gambar dari gereja pada 1524, berargumen bahwa gambar dapat mengalihkan perhatian dari ibadah yang berpusat pada Firman Allah (A Commentary on True and False Religion, Zwingli, 1525). Calvin, dalam Institutes of the Christian Religion (1536), menolak gambar religius karena dianggap bertentangan dengan sifat Allah yang tak terlihat, meskipun ia lebih menekankan bahaya penyembahan berhala daripada menghancurkan gambar secara fisik. “Gambar religius berisiko menjerumuskan umat ke dalam penyembahan berhala,” tulis Calvin (Institutes, Buku I, Bab 11).
Berbeda dengan Carlstat, pendekatan Zwingli dan Calvin lebih sistematis, memengaruhi tradisi Reformed (Calvinis) di Swiss, Belanda, dan Skotlandia. Gereja-gereja Reformed mengosongkan interior gereja dari ikon, patung, dan dekorasi figural, menggantinya dengan dinding polos dan fokus pada khotbah. Sikap ini kontras
dengan Lutheranisme, yang mempertahankan beberapa gambar sebagai alat didaktik. Reformation and the Visual Arts (Christensen, 1992) mencatat bahwa perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara ikonoklasme radikal Carlstat dan pendekatan moderat Luther, dengan tradisi Reformed condong ke arah yang lebih anikonik.
Dampak pada Seni dan Ibadah Protestan
Pengaruh ikonoklasme dalam Protestantisme terlihat jelas dalam transformasi budaya visual gereja. Di wilayah Reformed, seperti Belanda pada abad ke-16 dan ke-17, gereja-gereja menjadi ruang minimalis, dengan fokus pada Firman Allah daripada seni religius. “Interior gereja Reformed dirancang untuk menghilangkan segala bentuk gambar yang dapat mengalihkan perhatian,” tulis Art and Religion in the Protestant Tradition (Dyrness, 2004). Namun, seni sekuler, seperti lukisan genre atau potret, berkembang pesat di kalangan Protestan, sebagaimana terlihat dalam karya seniman seperti Rembrandt, yang menghasilkan lukisan alkitabiah tanpa konteks ibadah (The Art of the Reformation, Koerner, 2004).
Dalam Lutheranisme, gambar religius tetap ada tetapi dibatasi pada fungsi pengajaran, seperti ilustrasi dalam katekismus atau lukisan di altar. Tradisi Anglikan, yang muncul di Inggris, mengambil jalan tengah, mempertahankan beberapa elemen visual seperti salib dan jendela kaca patri, tetapi menghindari penghormatan ikon ala Katolik. Konsili Nicea II, yang menegaskan ikon sebagai “jendela menuju ilahi” (The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Hussey, 2010), tidak diterima dalam Protestantisme, tetapi argumen teologisnya tetap menjadi rujukan untuk menolak ikonoklasme radikal seperti Carlstat.
Pengaruh Ikonoklasme dalam Protestantisme Kontemporer
Hingga abad ke-21, pengaruh ikonoklasme tetap terlihat dalam berbagai denominasi Protestan, meskipun dengan variasi. Dalam gereja-gereja evangelical dan non-denominasi, yang berkembang di Amerika Serikat dan global, sikap anikonik tetap kuat. Banyak gereja evangelical menghindari ikon, patung, atau gambar religius, dengan fokus pada ibadah yang berpusat pada khotbah dan musik kontemporer. “Gereja-gereja modern sering kali mengadopsi estetika sederhana untuk menekankan keintiman spiritual tanpa perantara visual,” tulis Worship in the Modern World (White, 2000). Ini mencerminkan warisan ikonoklasme Reformed, meskipun tanpa kekerasan fisik seperti pada masa Carlstat.
Sebaliknya, beberapa denominasi Protestan, seperti Lutheran dan Anglikan, tetap menggunakan gambar religius dalam konteks terbatas. Gereja-gereja Anglikan, misalnya, sering mempertahankan jendela kaca patri atau salib sebagai bagian dari tradisi liturgi mereka, tetapi tanpa penghormatan seperti dalam Katolik atau Ortodoks. “Penggunaan gambar dalam Anglikanisme adalah kompromi antara estetika dan teologi,” catat The Oxford History of Anglicanism (Sachs, 2017). Sementara itu, gerakan ekumenis abad ke-20, seperti dialog antara Gereja Katolik dan Protestan, telah mendorong beberapa denominasi untuk mengevaluasi ulang sikap mereka terhadap ikon, meskipun Nicea II tetap menjadi titik perbedaan teologis.
Pengaruh ikonoklasme juga terlihat dalam budaya visual Protestan modern. Film, media digital, dan seni kontemporer sering digunakan untuk menyampaikan pesan alkitabiah, tetapi tanpa fungsi sakral seperti ikon dalam tradisi Katolik atau Ortodoks. Katekismus Gereja Katolik (KGK 2132) menegaskan bahwa ikon tidak bertentangan dengan perintah pertama, sebuah pandangan yang terus ditolak oleh beberapa kelompok Protestan yang mewarisi semangat anikonik Calvin. Namun, di kalangan Protestan liberal, seperti beberapa gereja Metodis, ada keterbukaan terhadap seni religius sebagai ekspresi iman, meskipun tidak dalam konteks ibadah formal.
Ketegangan antara Teologi dan Budaya
Pengaruh ikonoklasme dalam Protestantisme mencerminkan ketegangan antara teologi yang berpusat pada Firman Allah dan kebutuhan akan ekspresi budaya. Carlstat mewakili ekstrem ikonoklasme yang menolak semua gambar, tetapi kegagalannya menunjukkan bahwa pendekatan radikal tidak berkelanjutan. Zwingli dan Calvin memberikan kerangka yang lebih sistematis, memengaruhi tradisi Reformed yang mendominasi gereja-gereja Protestan di Eropa dan Amerika. Namun, Lutheranisme dan Anglikanisme menunjukkan bahwa gambar dapat memiliki tempat dalam ibadah Kristen tanpa melanggar prinsip teologis, sejalan dengan semangat moderat Luther.
Warisan ikonoklasme Bizantium, khususnya argumen Hieria yang dipatahkan Nicea II, tetap relevan sebagai latar belakang teologis. “Ikonoklasme adalah pengkhianatan terhadap misteri Inkarnasi,” tulis The Orthodox Church in the Byzantine Empire (Hussey, 2010), sebuah pandangan yang kontras dengan sikap anikonik Protestan. Meskipun Protestantisme tidak menerima Nicea II, dialog ekumenis modern telah membuka ruang untuk memahami peran seni dalam iman, meskipun dengan batasan. Pengaruh ikonoklasme dalam Protestantisme kontemporer terlihat dalam estetika minimalis gereja-gereja evangelical, tetapi juga dalam keterbukaan beberapa denominasi terhadap seni sebagai alat pengajaran.
Kesimpulan
Ikonoklasme, yang berakar dari krisis Bizantium dan dihidupkan kembali oleh Carlstat, telah membentuk sikap Protestantisme terhadap gambar religius dari Reformasi hingga masa kini. Kegagalan Carlstat menunjukkan keterbatasan pendekatan radikal, sementara pandangan Zwingli dan Calvin membentuk tradisi Reformed yang anikonik. Lutheranisme dan Anglikanisme menawarkan jalan tengah, menggunakan gambar sebagai alat didaktik tanpa penghormatan sakral.
Hingga abad ke-21, gereja-gereja Protestan, terutama evangelical, mewarisi semangat ikonoklasme melalui estetika minimalis, sementara dialog ekumenis mendorong keterbukaan terhadap seni religius. Konsili Nicea II, dengan doktrin Inkarnasinya (Denzinger-Hünermann, DH 600–603; Katekismus Gereja Katolik, KGK 2132), tetap menjadi rujukan teologis yang menantang sikap anikonik Protestan. Pengaruh ikonoklasme dalam Protestantisme menunjukkan bahwa ketegangan antara Firman dan gambar terus membentuk identitas iman Kristen.3
Penyembahan dalam Ajaran Gereja Katolik
Penyembahan dalam ajaran Gereja Katolik adalah tindakan spiritual yang secara absolut terarah kepada Allah Tritunggal. Namun, ajaran Gereja dengan tegas menyatakan bahwa puncak, sumber, dan pusat dari seluruh kehidupan penyembahan adalah kurban Ekaristi. Di sinilah satu-satunya tindakan penyembahan (latria) yang sempurna terjadi, karena Kristus sendiri yang mempersembahkan diri-Nya kepada Bapa. Semua bentuk devosi, doa, dan bahkan penggunaan gambar atau patung suci harus dipahami dalam kerangka ini: sebagai sarana yang mempersiapkan, mendukung, dan mengarahkan umat kepada misteri Ekaristi.
Artikel ini untuk menegaskan sentralitas Ekaristi dalam penyembahan Katolik, dan dengan demikian menepis tuduhan penyembahan berhala secara lebih fundamental. Dengan merujuk pada Kitab Suci, Katekismus Gereja Katolik (KGK), dan dokumen Konsili, artikel ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap patung tidak hanya keliru secara terminologis (membedakan latria dan dulia), tetapi juga secara teologis, karena mengabaikan fokus utama penyembahan Katolik: Kristus yang hadir secara nyata dalam Ekaristi.
1. Makna Penyembahan: Latria yang Berpuncak pada Ekaristi
Penyembahan dalam teologi Katolik, yang disebut latria, adalah penghormatan tertinggi yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Katekismus Gereja Katolik (KGK 2096) mendefinisikannya sebagai “tindakan keadilan yang memberikan kepada Allah kemuliaan yang menjadi hak-Nya.” Namun, tindakan latria ini menemukan ekspresi tertingginya bukan dalam doa pribadi atau devosi, melainkan dalam liturgi.
Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium (no. 7) menegaskan bahwa liturgi, terutama kurban Ekaristi, adalah tindakan penyembahan yang paling agung, karena merupakan karya Kristus sendiri dan Tubuh-Nya, Gereja. Di sinilah penyembahan sejati terjadi. Oleh karena itu, semua bentuk penghormatan lain, seperti dulia (kepada para kudus) dan hyperdulia (kepada Bunda Maria), bersifat sekunder dan selalu mengarah pada kemuliaan Allah yang dirayakan secara paripurna dalam Ekaristi.
2. Dasar Teologis: Ekaristi sebagai Satu-satunya Penyembahan yang Sempurna
Dasar teologis penyembahan Katolik adalah perintah Allah sendiri: “Akulah Tuhan, Allahmu… jangan ada ilah lain di hadapan-Ku” (Keluaran 20:2-3). Yesus menggenapi perintah ini dan memberikan cara baru untuk menyembah Bapa, yakni di dalam Dia. Puncaknya adalah perintah-Nya pada Perjamuan Terakhir: “Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku” (Lukas 22:19). Perintah ini mendasari Ekaristi sebagai pusat penyembahan Perjanjian Baru.
Konsili Vatikan II menyebut Ekaristi sebagai “sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani” (Lumen Gentium, no. 11). Ini berarti bahwa Ekaristi bukanlah salah satu dari banyak bentuk penyembahan, melainkan mata air dari mana semua devosi lain mengalir dan puncak ke mana semuanya harus diarahkan. Penggunaan patung, yang ditegaskan oleh Konsili Nicea II (787 M), harus dipahami dalam terang ini. Patung atau ikon tidak memiliki nilai penyembahan dalam dirinya sendiri; nilainya terletak pada kemampuannya untuk mengarahkan pikiran dan hati kepada Kristus dan para kudus, yang persatuannya dengan kita dirayakan secara sakramental dalam Ekaristi.
3. Bentuk-Bentuk Ibadah yang Berpusat pada Ekaristi
Semua wujud spiritualitas Katolik pada hakikatnya bersifat Ekaristis.
- Liturgi Ekaristi: Satu-satunya Tindakan Latria yang Sempurna: Ini adalah inti penyembahan. Di sini, umat tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga berpartisipasi dalam kurban Kristus yang satu, kekal, dan sempurna (KGK 1367). Salib di altar atau gambar suci di dalam gereja berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada realitas kurban yang sedang terjadi di altar, bukan sebagai objek penyembahan yang terpisah.
- Doa, Devosi, dan Kehidupan Beriman: Doa Rosario, novena, atau adorasi Sakramen Mahakudus adalah bentuk-bentuk devosi yang secara eksplisit bersifat Ekaristis. Adorasi adalah perpanjangan dari Misa, di mana kita menyembah Kristus yang sama yang hadir dalam Ekaristi. Doa Rosario merenungkan misteri kehidupan Kristus, yang puncaknya adalah misteri Paskah yang kita rayakan dalam Ekaristi. Bahkan persembahan hidup sehari-hari (Roma 12:1) menjadi bermakna ketika disatukan dengan persembahan Kristus di altar.
4. Peran Patung: Subordinat dan Pelayan Misteri Ekaristi
Dalam kerangka teologi yang berpusat pada Ekaristi, peran patung menjadi sangat jelas dan subordinat (di bawah dan melayani).
- Bukan Tujuan, tetapi Penunjuk Jalan: KGK (2132) menyatakan, “penghormatan kepada gambar-gambar suci adalah penghormatan kepada pribadi yang digambarkan.” Dalam konteks liturgi, pribadi ini (Kristus, Maria, atau para kudus) hadir dan relevan karena hubungannya dengan Misteri Paskah yang dirayakan di altar. Patung adalah pembantu visual yang mengarahkan iman umat kepada misteri sentral Ekaristi, bukan mengalihkannya.
- Teologi Inkarnasi Menuju Sakramen: Teologi inkarnasi (Allah menjadi manusia) memang membenarkan penggambaran Kristus. Namun, Inkarnasi itu sendiri mencapai tujuannya dalam kurban Paskah, yang dihadirkan kembali dalam Ekaristi. Jadi, patung mengingatkan kita pada Inkarnasi yang memuncak pada kehadiran nyata Kristus di altar.
5. Tanggapan terhadap Kritik dari Perspektif Ekaristis
Dengan menempatkan Ekaristi sebagai pusat, kritik terhadap penggunaan patung dapat dijawab dengan lebih tegas:
- Tuduhan Penyembahan Berhala: Tuduhan ini menjadi tidak relevan. Umat Katolik tidak menyembah patung karena fokus utama penyembahan (latria) mereka secara definitif diarahkan pada Kristus yang hadir dalam Sakramen Ekaristi di altar.
Mustahil menyembah patung kayu atau batu ketika pada saat yang sama mengakui kehadiran Allah yang hidup dan nyata hanya beberapa meter di depan mereka dalam rupa roti dan anggur.
- Liturgi sebagai Formalitas: Justru karena penyembahan terpusat pada tindakan nyata Kristus dalam Ekaristi, maka liturgi bukanlah formalitas kosong. Patung dan seni suci lainnya berfungsi untuk memperkaya dan memperdalam pengalaman akan realitas agung yang terjadi di altar, bukan menutupinya dengan ritualisme.
6. Kesimpulan
Penyembahan sejati dalam Gereja Katolik adalah tindakan cinta kepada Allah Tritunggal yang secara eksklusif menemukan puncaknya dalam kurban Ekaristi. Ini adalah satu-satunya tindakan latria yang sempurna di dunia. Penggunaan patung, yang berakar pada teologi Inkarnasi dan ditegaskan oleh Tradisi Suci, adalah alat bantu yang sah dan bermanfaat, tetapi perannya selalu sekunder dan melayani. Patung membantu mengarahkan hati dan pikiran kepada Kristus dan misteri keselamatan-Nya, yang dirayakan dan dihadirkan secara nyata di atas altar.
Dengan demikian, jawaban paling fundamental terhadap tuduhan penyembahan berhala bukanlah sekadar pembedaan antara latria dan dulia, melainkan iman Gereja yang mendalam dan tak tergoyahkan akan Kehadiran Nyata Kristus dalam Ekaristi. Di hadapan misteri ini, semua gambar dan patung hanyalah gema dan bayangan yang menunjuk pada Realitas itu sendiri, satu-satunya yang layak disembah.4