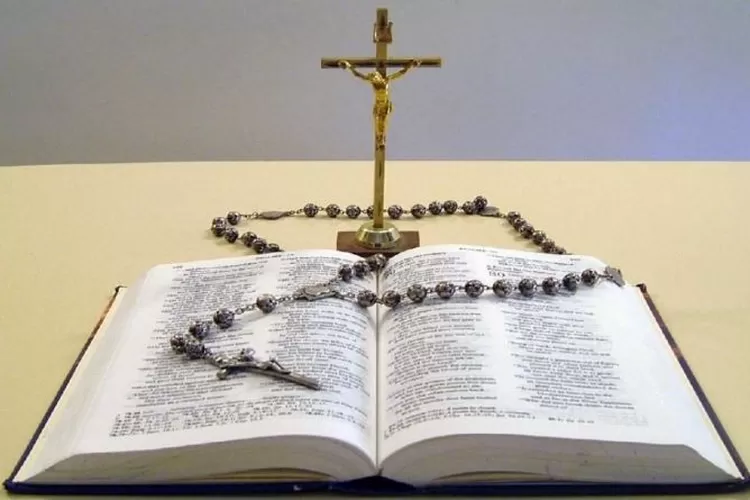LIVE DKC [99-2025] SENIN, 11 AGUSTUS 2025 PUKUL 14:00 WIB: KRISTEN NEBENG, ALIRAN KEPERCAYAAN??? @AlbertRumampuk @Patris_Smith
Protestanisme: Kristen Nebeng, Aliran Kepercayaan??
Protestanisme sering terlihat seperti adik kecil yang meminjam pakaian kakaknya – dalam hal ini Gereja Katolik -lalu menggunting, mewarnai, dan mengklaimnya sebagai desain orisinal. Dari Kitab Suci, kalender liturgi, hari raya seperti Natal dan Paskah, simbol salib, hingga struktur gereja, Protestanisme mengambil fondasi yang disusun rapi oleh Gereja Katolik selama berabad-abad, lalu memodifikasinya dengan gaya seolah-olah mereka menciptakan sesuatu yang baru. Mereka menegaskan bahwa iman kepada Yesus adalah inti Kekristenan sejati, tetapi apakah “Kristen” di KTP atau Katolik yang lebih layak menyandang gelar Kristen sejati? Artikel ini menguraikan, dengan bukti dari sumber-sumber kredibel, ketergantungan Protestanisme pada warisan Katolik, sambil menjawab pertanyaan tersebut dengan analisis teologis, konteks Indonesia, dan perspektif kontemporer.
1. Kitab Suci: Pinjam Buku, Buang Catatan Kakinya
Protestanisme menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi (sola scriptura), tetapi jarang mengakui peran Gereja Katolik dalam menyusunnya. Kanon Kitab Suci, khususnya Perjanjian Baru (27 kitab) dan kitab Deuterokanonika seperti Tobit dan Makabe, ditetapkan melalui Konsili Roma (382 M), Hippo (393 M), dan Kartago (397 M). Henry G. Graham menegaskan, “Gereja Katolik, melalui konsili-konsili ini, menentukan kitab mana yang dianggap ilahi, dan biara-biara Katolik menyalinnya selama berabad-abad untuk menjaga keutuhan teks” (Graham, 1997, hlm. 50).
Tanpa usaha ini, Alkitab tidak akan ada dalam bentuk yang kita kenal sekarang.
Martin Luther, tokoh Reformasi, mengambil kanon ini, tetapi membuang kitab Deuterokanonika karena dianggap tidak mendukung teologinya. Ia juga mempertanyakan Kitab Yakobus, menyebutnya “surat jerami” karena menekankan perbuatan baik (Luther’s Works, Vol. 35, hlm. 395). Yakobus 2:17 (TB LAI, 2020) menyatakan, “Iman, jika tidak disertai perbuatan, pada hakekatnya adalah mati.” Luther merasa ayat ini bertentangan dengan sola fide (iman saja). F.F. Bruce menjelaskan, “Kanon Alkitab adalah produk Gereja awal, yang dengan cermat memilih teks-teks yang dianggap otentik” (Bruce, 1988, hlm. 105). Bapa Gereja seperti Ireneus dari Lyon (ca. 180 M) menegaskan, “Kami menerima Kitab Suci melalui Gereja, yang adalah penjaga iman sejati” (Ireneus, 1992, hlm. 112). Di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) mengakui peran historis Gereja Katolik dalam kanonisasi (Dokumen LAI: Sejarah Terjemahan Alkitab, 2015, hlm. 12). Protestanisme meminjam buku suci dari Katolik, tetapi membuang “catatan kaki” yang tidak disukai.
2. Kalender Liturgi: Jadwal Dicuri, tapi Direnovasi
Kalender liturgi, yang mengatur siklus ibadah seperti Adven, Natal, Prapaskah, dan Paskah, adalah ciptaan Gereja Katolik sejak Kekristenan awal. Konsili Nicea (325 M) menetapkan kerangka waktu liturgi, termasuk penentuan Paskah berdasarkan kalender lunar. Adolf Adam menjelaskan, “Kalender liturgi Katolik memberikan struktur waktu suci yang mengarahkan umat pada misteri Kristus” (Adam, 1981, hlm. 25). Denominasi Protestan seperti Lutheran dan Anglikan mengadopsi kerangka ini, meski dengan modifikasi, merayakan Natal pada 25 Desember dan Paskah sesuai kalender Gregorian, yang diperkenalkan Paus Gregorius XIII pada 1582.
Gereja-gereja Protestan di Indonesia, seperti Gereja Protestan di Indonesia Barat (GPIB) atau Gereja Kristen Indonesia (GKI), mengikuti siklus ini, tetapi mengabaikan hari raya seperti Hari Semua Orang Kudus (1 November), yang ada sejak abad ke-8. F.L. Cross mencatat, “Banyak tradisi Protestan mengambil kalender liturgi Katolik, tetapi menyesuaikannya dengan teologi mereka” (Cross & Livingstone, 2005, hlm. 1443). Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium (no. 102) menyatakan, “Gereja merayakan misteri Kristus melalui siklus tahunan, dari Inkarnasi hingga Kedatangan Kedua” (Konsili Vatikan II, 1965, hlm. 27). Protestanisme meminjam jadwal ini, tetapi mencoret bagian yang dianggap “terlalu Katolik.”
3. Hari Raya, Natal, dan Paskah: Pesta Ikut, Menu Dipilih
Hari raya seperti Natal dan Paskah adalah warisan Katolik yang diadopsi Protestan tanpa ragu. Natal ditetapkan pada 25 Desember sejak abad ke-4 untuk menggantikan perayaan pagan seperti Saturnalia. The Catholic Encyclopedia menjelaskan, “Tanggal ini dipilih untuk menguduskan waktu bagi umat Kristiani dan menandingi perayaan kafir” (1913, Vol. 3, hlm. 724). Paskah diatur melalui Konsili Nicea (325 M). Paul F. Bradshaw mencatat, “Penetapan Paskah berdasarkan kalender lunar adalah keputusan Gereja awal untuk menyatukan umat” (Bradshaw, 2010, hlm. 82). Di Indonesia, gereja-gereja Protestan seperti HKBP merayakan Natal dan Paskah, tetapi mengabaikan hari raya seperti Pesta Corpus Christi atau Hari Asumsi Maria. Lukas 1:48 (TB LAI, 2020) menyatakan, “Ia memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya, sebab sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.”
Agustinus dari Hippo (ca. 400 M) menegaskan, “Kita merayakan kelahiran Tuhan untuk mengingat kasih-Nya yang menjelma” (Sermo 191, 2008, hlm. 45). Protestanisme mengambil tradisi perayaan ini, tetapi memilih-milih “menu” yang sesuai.
4. Simbol Salib: Ambil Simbol, Buang Krusifiksinya
Salib adalah simbol utama Kekristenan, digunakan Gereja Katolik sejak abad ke-2. Robin M. Jensen menulis, “Salib menjadi lambang utama iman Kristiani melalui tradisi Katolik yang kaya” (Jensen, 2017, hlm. 25). Protestan, terutama Lutheran dan Anglikan, mengadopsi salib, tetapi banyak yang menolak krusifiks karena dianggap “terlalu Katolik.” Di Indonesia, gereja-gereja seperti GKI lebih suka salib kosong. Yohanes 19:17 (TB LAI, 2020) mencatat, “Sambil memikul salib-Nya, Yesus pergi ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak.” Tertullianus (ca. 200 M) menyebutkan, “Kami membuat tanda salib di dahi sebagai tanda iman” (De Corona, 3:2, 2006, hlm. 32). Protestanisme mengambil simbol ini, tetapi mengubah maknanya.
5. Upacara Liturgi: Tata Ibadah Dipinjam, tapi Dirombak
Upacara liturgi Katolik, seperti Misa, sudah ada sejak abad ke-2. Yustinus Martir menggambarkan, “Kami berkumpul pada hari Minggu, membaca Kitab Suci, dan merayakan Ekaristi” (Apologi Pertama, ca. 150 M, bab 67, 1885, hlm. 186). Denominasi Protestan seperti Lutheran mengambil struktur ini, tetapi menghapus elemen seperti transubstansiasi. Frank C. Senn menjelaskan, “Liturgi Protestan sering kali merupakan adaptasi dari tradisi Katolik” (Senn, 1997, hlm. 260). Di Indonesia, GPIB menggunakan tata ibadah yang mirip, meski lebih sederhana (Panduan Liturgi GPIB, 2018, hlm. 22). Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium (no. 7) menegaskan, “Dalam liturgi, Kristus hadir dalam Sabda-Nya dan dalam Ekaristi” (Konsili Vatikan II, 1965, hlm. 7). Protestanisme mengambil resep liturgi Katolik, tetapi mengganti beberapa bahan.
6. Doktrin dan Praktik: Ambil Intinya, Buang Sisanya
Protestanisme mengadopsi doktrin inti seperti Trinitas dan Inkarnasi dari konsili Katolik seperti Nicea (325 M) dan Kalsedon (451 M). Katekismus Gereja Katolik menyatakan, “Pengakuan iman ini adalah warisan Gereja awal” (no. 185, 1994, hlm. 47). Namun, Protestan menolak transubstansiasi, penghormatan kepada Maria, dan tujuh sakramen. Yohanes 6:53–56 (TB LAI, 2020) menegaskan, “Jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.” Luther mempertahankan konsubstansiasi (Confessio Augustana, 1530, hlm. 20), Calvin menyebut Ekaristi sebagai “tanda rohani” (Institutio, IV.17.1, 2014, hlm. 102), dan Zwingli menganggapnya simbol (De Eucharistia, 1526, hlm. 15). Ignatius dari Antiokhia (ca. 110 M) menegaskan, “Ekaristi adalah daging Juruselamat kita Yesus Kristus” (Surat kepada Jemaat di Smirna, 7:1, 1987, hlm. 89). Di Indonesia, gereja-gereja Protestan menolak transubstansiasi, tetapi meminjam struktur Perjamuan Kudus (Panduan Liturgi GKI, 2018, hlm. 22). Protestanisme mengambil doktrin inti, tetapi membuang elemen yang dianggap “berlebihan.”
7. Struktur Gereja: Pinjam Fondasi, Bangun Rumah Lain
Struktur gereja Katolik, dengan uskup, imam, dan diakon, sudah ada sejak abad ke-1. Ignatius dari Antiokhia menulis, “Di mana ada uskup, di situ ada Gereja” (Surat kepada Jemaat di Magnesia, 6:1, 1987, hlm. 76). Anglikan mempertahankan struktur episkopal, sementara Lutheran dan Calvinis beralih ke model presbiterian. Alister E. McGrath menegaskan, “Struktur gereja Protestan sering kali merupakan adaptasi dari model Katolik” (McGrath, 2015, hlm. 205). Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium (no. 20) menyatakan, “Hierarki uskup, imam, dan diakon ditetapkan oleh Kristus melalui para Rasul” (Konsili Vatikan II, 1965, hlm. 38). Di Indonesia, HKBP menggunakan struktur sinodal (Anggaran Dasar HKBP, 2020, hlm. 10), tetapi konsep kepemimpinan rohani berakar pada Katolik.
8. Pengaruh Bapa-Bapa Gereja dan Konsili
Bapa-Bapa Gereja seperti Klemens dari Roma, Ireneus, dan Agustinus membentuk fondasi teologi Kristiani. Konsili Nicea (325 M) merumuskan Trinitas, Kalsedon (451 M) menegaskan Inkarnasi. Jaroslav Pelikan menulis, “Doktrin-doktrin ini adalah warisan Gereja Katolik yang menjadi dasar iman Kristen” (Pelikan, 1971, hlm. 120). Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum (no. 8) menyatakan, “Tradisi dan Kitab Suci bersama-sama menyampaikan Sabda Allah” (Konsili Vatikan II, 1965, hlm. 12). Jurnal Theological Studies (2020) mencatat, “Protestanisme tidak dapat lepas dari akar Katoliknya” (Rausch, 2020, hlm. 345). Journal of Ecumenical Studies (2023) menambahkan, “Gereja-gereja Protestan modern tetap menggunakan struktur liturgi dan doktrin Katolik” (Erling, 2023, hlm. 128).
9. Konteks Indonesia: Adaptasi dan Penyimpangan
Di Indonesia, gereja-gereja Protestan seperti HKBP, GKI, dan evangelikal-pentakostal menunjukkan ketergantungan pada tradisi Katolik, tetapi dengan penyimpangan. Gereja evangelikal sering mengabaikan kalender liturgi formal, tetapi merayakan Natal dan Paskah. Jurnal Teologi STT Jakarta (2022) mencatat, “Banyak gereja Protestan di Indonesia mengadopsi elemen Katolik seperti khotbah berbasis Kitab Suci, tetapi menolak sakramen seperti Pengurapan Orang Sakit” (Siregar, 2022, hlm. 45). KWI menegaskan pentingnya sakramen (Dokumen KWI: Sakramen dalam Kehidupan Gereja, 2020, hlm. 20).
10. Iman kepada Yesus dan Kristen Sejati: Katolik atau “Kristen” di KTP?
Protestanisme menegaskan bahwa iman kepada Yesus adalah inti Kekristenan. Yohanes 3:16 (TB LAI, 2020) menyatakan, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa.” Protestan, terutama evangelikal, sering mengklaim bahwa iman personal kepada Yesus menjadikan mereka “Kristen sejati,” kadang meremehkan Katolik sebagai “terlalu ritualistik.” Namun, Katolik memandang iman kepada Yesus tidak terpisah dari Gereja, sakramen, dan tradisi. Katekismus Gereja Katolik (no. 181) menyatakan, “Iman adalah tindakan pribadi, tetapi juga tindakan gerejawi, yang hidup dalam persekutuan dengan Gereja” (1994, hlm. 45).
Bapa Gereja seperti Klemens dari Roma (ca. 96 M) menegaskan, “Kita dipanggil untuk bersatu dalam Gereja yang didirikan oleh Kristus” (Surat kepada Jemaat di Korintus, 14:2, 1987, hlm. 15). Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium (no. 8) menyatakan, “Gereja Katolik adalah Gereja Kristus yang sejati, meskipun elemen kebenaran juga ditemukan di komunitas lain” (Konsili Vatikan II, 1965, hlm. 15). Di Indonesia, istilah “Kristen” di KTP sering merujuk pada Protestan, tetapi ini hanya label administratif, bukan penentu Kekristenan sejati. Dokumen KWI: Identitas Katolik (2018, hlm. 10) menegaskan, “Katolik adalah pewaris penuh tradisi apostolik, yang menjaga iman dan sakramen sejak Gereja awal.”
Protestanisme, dengan fokus pada iman personal, mengabaikan kelengkapan tradisi apostolik yang dijaga Katolik. Iman kepada Yesus dalam Katolik bukan hanya soal hati, tetapi juga persekutuan dengan Gereja yang didirikan Kristus (Matius 16:18, TB LAI, 2020: “Aku akan mendirikan jemaat-Ku”). Jadi, siapa Kristen sejati? Katolik, dengan warisan apostoliknya, memiliki klaim yang lebih kuat dibandingkan “Kristen” di KTP, yang sering kali hanya label tanpa kedalaman tradisi.
Kesimpulan: Nebeng dengan Percaya Diri Maksimal
Protestanisme meminjam fondasi Gereja Katolik: Kitab Suci, kalender liturgi, hari raya, simbol salib, liturgi, doktrin inti, dan struktur gereja. Di Indonesia, gereja-gereja Protestan menunjukkan ketergantungan serupa, meski dengan adaptasi lokal. Mereka menegaskan iman kepada Yesus sebagai inti, tetapi mengabaikan tradisi apostolik yang dijaga Katolik. Alkitab? Terima kasih konsili Katolik. Natal? Warisan Katolik. Salib? Pinjaman dari Katolik. Protestanisme mengambil fondasi Katolik, menambahkan bumbu sola scriptura, dan mengklaimnya sebagai ciptaan baru. Katolik, dengan kelengkapan tradisi dan sakramen, lebih layak disebut Kristen sejati ketimbang label “Kristen” di KTP. Jadi, ya, Protestanisme nebeng – dan melakukannya dengan percaya diri maksimal.1
Iman SKSD ala Protestantisme: Ilusi Hubungan Pribadi dengan Kristus (???)
Fenomena Sok Kenal Sok Dekat (SKSD) dalam literasi iman Protestan menonjolkan hubungan personal dengan Yesus Kristus yang berfokus pada pengalaman emosional dan interpretasi individual terhadap Alkitab. Pendekatan ini, yang sering dianut dalam aliran evangelikal dan pentakostal, mengklaim kedekatan dengan Yesus tanpa selalu mempertimbangkan konteks historis, teologis, dan eklesiologis yang telah membentuk pemahaman Kekristenan selama dua milenium.
Artikel ini mengkritisi pendekatan SKSD dalam Protestantisme, khususnya dalam memahami pribadi Yesus Kristus, dengan menawarkan perspektif Katolik yang lebih terintegrasi. Berlandaskan pada sumber-sumber teologis kredibel, termasuk dokumen resmi Gereja Katolik dan Kitab Suci, serta karya-karya teologis mutakhir, artikel ini mengupas akar masalah SKSD, implikasinya terhadap Kristologi, dan pentingnya kembali ke Tradisi Suci serta otoritas Gereja untuk memahami Yesus secara utuh.
1. Anatomi SKSD: Hubungan Pribadi yang Mengabaikan Fondasi
Pendekatan SKSD dalam Protestantisme menekankan pengalaman subjektif, seperti doa spontan, puji-pujian, atau pengakuan iman individualistis, yang didasarkan pada prinsip sola scriptura—Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Prinsip ini menolak Tradisi Suci dan Magisterium Gereja. Namun, teolog Katolik Yves Congar dalam Tradition and Traditions menegaskan, “Kitab Suci tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu dibaca dan ditafsirkan dalam terang Tradisi yang hidup di dalam Gereja” (Congar, 1966, hlm. 45). SKSD cenderung memisahkan Yesus dari konteks-Nya sebagai Mesias Yahudi dan pendiri Gereja, mengubah-Nya menjadi figur yang “fleksibel” sesuai kebutuhan emosional individu.
Sebagai contoh, banyak komunitas Protestan menonjolkan Yesus sebagai “sahabat” berdasarkan Yohanes 15:15 (TB LAI 2017): “Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku telah menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku telah Kuberitahukan kepadamu.” Namun, ayat ini sering diambil di luar konteksnya. Joseph Ratzinger (Paus Benediktus XVI) dalam Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration menjelaskan, “Persahabatan dengan Yesus bukanlah hubungan kasual; ini adalah panggilan untuk mengikuti Dia dalam ketaatan penuh kepada kehendak Bapa, yang diwujudkan melalui Gereja” (Ratzinger, 2007, hlm. 112). Hubungan dengan Yesus menuntut komitmen pada kebenaran ilahi yang diwahyukan melalui Alkitab dan Tradisi, bukan sekadar perasaan hangat.
2. Kristologi Protestan: Yesus yang Dibentuk Ulang
Pendekatan SKSD sering menghasilkan Kristologi yang terdistorsi, di mana Yesus dipahami sesuai kebutuhan atau preferensi pribadi. Oscar Cullmann dalam The Christology of the New Testament menegaskan bahwa pemahaman tentang Yesus harus berakar pada pengakuan-Nya sebagai Mesias, Anak Allah, dan Sabda yang menjelma, dalam konteks sejarah Yahudi dan pengajaran apostolik (Cullmann, 1959, hlm. 320). Namun, dalam SKSD, Yesus sering direduksi menjadi figur yang melayani kebutuhan individual – seperti penyembuh, pemberi berkat materi, atau pendengar keluh kesah – tanpa memahami dimensi penuh inkarnasi, sengsara, dan kebangkitan-Nya.
Salah satu contoh nyata adalah penolakan banyak denominasi Protestan terhadap doktrin Real Presence dalam Ekaristi. Dalam pandangan Protestan, terutama aliran Zwinglian, Perjamuan Kudus dipahami sebagai simbol belaka. Sebaliknya, Katekismus Gereja Katolik (terjemahan KWI, 1995) menegaskan, “Dalam Sakramen Ekaristi, Kristus memberikan Tubuh dan Darah yang sama yang telah Ia serahkan di salib untuk keselamatan umat manusia” (KGK, 1366). Penolakan ini menunjukkan bagaimana SKSD mengabaikan aspek sakramental dari kehadiran Yesus, yang menjadi inti hubungan dengan-Nya dalam Tradisi Katolik.
Teolog kontemporer Brant Pitre dalam Jesus and the Last Supper menegaskan bahwa Ekaristi adalah “pemenuhan janji Yesus untuk tetap hadir di tengah umat-Nya” (Pitre, 2015, hlm. 412). Yohanes 6:53-54 (TB LAI 2017) menggarisbawahi pentingnya Ekaristi: “Jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.” Penolakan terhadap makna harafiah ayat ini dalam banyak tradisi Protestan mencerminkan kecenderungan SKSD untuk memilih interpretasi yang lebih “nyaman” secara emosional.
3. Bahaya SKSD: Subjektivisme dan Fragmentasi Iman
Pendekatan SKSD membawa risiko subjektivisme, di mana pengalaman pribadi menjadi ukuran utama kebenaran iman. Hans Urs von Balthasar dalam The Office of Peter and the Structure of the Church mengkritik kecenderungan ini: “Iman yang tidak berakar pada otoritas apostolik cenderung menjadi proyeksi diri, bukan pengakuan akan kebenaran objektif Kristus” (Balthasar, 1986, hlm. 78). Dalam konteks Protestan, subjektivisme ini terlihat dari proliferasi denominasi – diperkirakan lebih dari 40.000 pada 2020 menurut World Christian Encyclopedia (Barrett et al., 2020) – yang masing-masing mengklaim kebenaran berdasarkan interpretasi Alkitab mereka sendiri.
Sebaliknya, Gereja Katolik menawarkan pendekatan terintegrasi melalui triad Alkitab, Tradisi Suci, dan Magisterium. Dokumen Konsili Vatikan II, Dei Verbum (terjemahan KWI, 1965), menegaskan, “Tradisi Suci dan Kitab Suci membentuk satu deposit iman yang suci, yang dipercayakan kepada Gereja untuk diwartakan dan dijaga” (DV, 10). Pendekatan ini memastikan bahwa pemahaman tentang Yesus tidak terjebak dalam subjektivisme, tetapi diarahkan oleh otoritas apostolik yang menjamin kesatuan iman.
Teolog Matthew Levering dalam Did Jesus Rise from the Dead? menegaskan bahwa kebangkitan Yesus hanya dapat dipahami secara utuh dalam konteks komunitas Gereja yang didirikan-Nya: “Kebangkitan bukan sekadar peristiwa historis, tetapi realitas yang terus hidup dalam Ekaristi dan pengajaran Gereja” (Levering, 2019, hlm. 189). Pendekatan SKSD, yang sering mengabaikan peran Gereja, gagal menangkap dimensi komunal dan sakramental dari iman kepada Yesus.
4. Tantangan bagi SKSD: Kembali ke Akar Apostolik
Untuk mengatasi keterbatasan SKSD, Protestantisme perlu kembali ke akar apostolik Kekristenan, yang tidak hanya berfokus pada Alkitab, tetapi juga pada Tradisi yang telah membentuk pemahaman tentang Yesus. John Henry Newman dalam An Essay on the Development of Christian Doctrine menegaskan, “Iman Kristen berkembang bukan dengan menciptakan hal baru, tetapi dengan memperdalam pengertian akan wahyu yang telah diberikan melalui Gereja” (Newman, 1845, hlm. 201). Gereja Katolik, dengan otoritasnya yang berasal dari Petrus, menyediakan kerangka kokoh untuk memahami Yesus sebagai Tuhan, Juruselamat, dan Hakim yang hadir dalam sakramen.
Teolog Scott Hahn dalam The Lamb’s Supper menegaskan bahwa Ekaristi adalah “puncak dan sumber kehidupan Kristen,” di mana umat bertemu dengan Yesus secara nyata (Hahn, 1999, hlm. 134). Matius 16:18 (TB LAI 2017) menegaskan otoritas Gereja: “Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya.” Dengan mengintegrasikan Alkitab, Tradisi, dan Magisterium, Gereja Katolik menawarkan hubungan dengan Yesus yang tidak hanya personal, tetapi juga objektif dan komunal.
5. Kritik dan Refleksi: SKSD sebagai Cermin Ketidaksabaran Modern
Pendekatan SKSD mencerminkan ketidaksabaran modern terhadap proses pembelajaran iman yang mendalam. Dalam budaya instan, di mana kepuasan segera menjadi tolok ukur, SKSD menawarkan “Yesus” yang mudah diakses tanpa memerlukan disiplin rohani atau refleksi teologis. Paus Fransiskus dalam ensiklik Lumen Fidei (terjemahan KWI, 2013) mengingatkan, “Iman bukanlah pelarian dari dunia, tetapi panggilan untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri Kristus melalui Gereja” (Fransiskus, 2013, hlm. 46). Pendekatan Katolik menuntut kesabaran untuk memahami Yesus melalui doa, sakramen, dan pengajaran Gereja, bukan sekadar perasaan pribadi.
Edward Sri dalam Who Am I to Judge? menyoroti bahaya relativisme dalam pendekatan iman modern: “Tanpa kebenaran objektif yang dipegang oleh Gereja, iman menjadi sekadar preferensi pribadi, bukan panggilan untuk menyesuaikan hidup dengan kehendak Allah” (Sri, 2021, hlm. 92). Pendekatan SKSD, dengan fokusnya pada pengalaman individu, sering gagal menghormati misteri Kristus yang lebih luas, yang hanya dapat dipahami melalui komunitas Gereja.
Kesimpulan
Pendekatan SKSD dalam Protestantisme, meskipun penuh semangat, sering gagal menangkap kedalaman pribadi Yesus Kristus karena keterbatasannya pada pengalaman subjektif dan penolakan terhadap Tradisi Suci. Dengan mengabaikan otoritas apostolik dan dimensi sakramental, SKSD menghasilkan Kristologi yang terfragmentasi dan rentan terhadap subjektivisme. Sebaliknya, Gereja Katolik menawarkan pemahaman yang lebih utuh tentang Yesus melalui integrasi Alkitab, Tradisi, dan Magisterium, yang memastikan hubungan dengan Kristus yang autentik dan terarah. Bagi umat Protestan yang ingin benar-benar “kenal” dengan Yesus, sudah saatnya mereka membaca “catatan kaki” sejarah Gereja – dan berhenti berpura-pura sudah paham semuanya.2
Makelar Iman dalam Protestantisme: Penjelasan dan Bukti Menurut Ajaran Gereja Katolik
Konsep “makelar iman” tidak disebut secara eksplisit dalam dokumen resmi Gereja Katolik, tetapi dapat dipahami sebagai kritik terhadap pendekatan individualistik dan subjektif terhadap iman, yang sering diasosiasikan dengan tradisi Protestantisme, terutama prinsip “sola scriptura.” Dalam pandangan Katolik, iman adalah anugerah ilahi yang disampaikan melalui tiga pilar: Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium Gereja. Pendekatan Protestantisme, yang mengutamakan otoritas tunggal Kitab Suci dan penafsiran pribadi, dipandang berpotensi merusak keutuhan iman, membuka peluang bagi subjektivisme, fragmentasi, dan penyimpangan doktrinal.
Artikel ini menguraikan perspektif Gereja Katolik, menyajikan bukti dari dokumen resmi, sejarah, dan teologi, serta menyoroti implikasi dari pendekatan tersebut dalam konteks keimanan Kristen.
1. Landasan Ajaran Katolik tentang Iman
Gereja Katolik memandang iman sebagai karunia Allah yang diwahyukan melalui Kitab Suci, diperdalam oleh Tradisi Suci, dan diawasi oleh Magisterium, otoritas pengajar Gereja. Konsili Vatikan II, dalam konstitusi dogmatis Dei Verbum, menegaskan keterkaitan ketiga elemen ini:
“Tradisi Suci dan Kitab Suci membentuk satu depositum suci Firman Allah, yang dipercayakan kepada Gereja. Dengan berpegang teguh pada ini, seluruh umat suci, yang bersatu dengan para uskupnya, tetap setia dalam ajaran, kehidupan, dan ibadat, serta dalam mewariskan warisan iman yang sama kepada semua generasi.” (Konferensi Waligereja Indonesia, Dokumen Konsili Vatikan II, Jakarta: KWI, 2003, hlm. 44)
Katekismus Gereja Katolik (KGK) menambahkan:
“Iman bukanlah suatu tindakan terisolasi. Tidak seorang pun dapat beriman sendirian, sebagaimana tidak seorang pun dapat hidup sendirian. Iman diterima dari Gereja dan disampaikan melalui Gereja, yang adalah ibu dan guru kita.” (Konferensi Waligereja Indonesia, Katekismus Gereja Katolik, Jakarta: KWI, 1995, hlm. 54, no. 166)
Jelaslah bahwa iman, dalam pandangan Katolik, bukan urusan pribadi yang dapat dibentuk sekehendak hati. Menganggapnya demikian berisiko menjadikan seseorang “makelar iman,” yang seenaknya menentukan isi keimanan tanpa bimbingan otoritas apostolik.
2. Prinsip “Sola Scriptura” dalam Protestantisme
Reformasi Protestantisme abad ke-16, yang dipelopori Martin Luther, mengusung prinsip “sola scriptura,” menegaskan Kitab Suci sebagai otoritas tunggal dalam iman dan praktik keagamaan. Sejarawan James Atkinson mencatat pandangan Luther:
“Luther menegaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran ilahi, dan setiap orang Kristen, dengan bimbingan Roh Kudus, berhak menafsirkannya tanpa campur tangan otoritas eksternal seperti Gereja atau tradisi.” (Atkinson, James, Luther and the Reformation, London: Penguin Books, 1962, hlm. 112)
Meski bertujuan membebaskan umat dari penyalahgunaan otoritas Gereja pada masa itu, pendekatan ini, menurut Katolik, membuka celah berbahaya. Tanpa Magisterium, penafsiran pribadi Alkitab rentan menghasilkan pandangan yang saling bertentangan. Teolog Katolik Louis Bouyer menyoroti:
“Dengan menolak Magisterium, Protestantisme telah menyerahkan iman kepada kehendak individu, menciptakan situasi di mana kebenaran ilahi menjadi subjek penafsiran pribadi, sering kali dipengaruhi oleh bias, emosi, atau kurangnya pengetahuan historis dan teologis.” (Bouyer, Louis, The Spirit and Forms of Protestantism, Westminster: The Newman Press, 1956, hlm. 190)
Di sinilah muncul bayangan “makelar iman”: individu atau kelompok yang mengklaim otoritas tanpa dasar apostolik, membentuk keimanan seolah-olah barang dagangan yang disesuaikan dengan selera pribadi.
3. Bukti Sejarah: Fragmentasi dan Perpecahan
Konsekuensi nyata dari “sola scriptura” adalah pecahnya kesatuan iman. Sejak Reformasi, ribuan denominasi Protestan bermunculan—Lutheran, Calvinis, Baptis, Pentakosta, dan lainnya – masing-masing mengklaim kebenaran berdasarkan penafsiran Alkitab mereka. Sejarawan Lewis W. Spitz mencatat:
“Dalam kurun waktu satu abad setelah Luther, ratusan sekte dan denominasi muncul, masing-masing dengan doktrin yang berbeda tentang pembaptisan, Perjamuan Kudus, predestinasi, dan struktur gereja, menunjukkan bahwa ‘sola scriptura’ tidak menghasilkan kesatuan, tetapi perpecahan.” (Spitz, Lewis W., The Protestant Reformation, St. Louis: Concordia Publishing House, 1985, hlm. 321)
Gereja Katolik menanggapi tantangan ini melalui Konsili Trente (1545–1563). Dalam Decree on Sacred Scripture and Tradition, konsili menegaskan:
“Kebenaran dan disiplin yang terkandung dalam Kitab Suci dan Tradisi Suci, yang diterima dari para Rasul, harus dipegang dengan hormat yang sama, dan Gereja, melalui otoritasnya, berwenang untuk menafsirkannya demi menjaga kesatuan iman.” (Tanner, Norman P., Decrees of the Ecumenical Councils, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990, hlm. 657).
Fragmentasi ini menjadi bukti bahwa, tanpa otoritas pengajar, iman berisiko menjadi komoditas di pasar rohani, di mana “makelar” bebas menawarkan versi-versi kebenaran yang saling berselisih.
4. Iman sebagai Anugerah Ilahi
Gereja Katolik menegaskan bahwa iman adalah karunia Allah, bukan produk manusia yang dapat dibentuk sesuka hati. Katekismus Gereja Katolik menyatakan:
“Untuk hidup, bertumbuh, dan bertahan dalam iman, kita harus memeliharanya dengan Firman Allah; kita harus memohon kepada Tuhan agar menumbuhkannya; iman harus bekerja melalui kasih, didukung oleh harapan, dan berakar dalam iman Gereja.” (Konferensi Waligereja Indonesia, Katekismus Gereja Katolik, Jakarta: KWI, 1995, hlm. 54, no. 162).
Teolog Yves Congar menambahkan:
“Iman yang sejati tidak dapat dipisahkan dari Gereja, karena Kristus telah menitipkan wahyu-Nya kepada para Rasul dan penerus mereka. Ketika seseorang mengabaikan Tradisi dan otoritas Gereja, iman berisiko menjadi cerminan dari ego manusia, bukan cerminan kehendak Allah.” (Congar, Yves, The Meaning of Tradition, New York: Hawthorn Books, 1964, hlm. 75)
Kontras dengan ini, beberapa kalangan Protestan cenderung mengemas iman berdasarkan penafsiran pribadi, menyesuaikannya dengan kebutuhan emosional atau budaya. Hasilnya, iman menjadi seperti barang di toko rohani, di mana “makelar” menjajakan versi-versi berbeda: satu menolak sakramen, yang lain menciptakan doktrin baru, merendahkan anugerah ilahi menjadi produk sesaat.
5. Peran Magisterium: Benteng Iman
Magisterium, yang terdiri dari Paus dan para uskup dalam kesatuan dengannya, bertugas menjaga dan menafsirkan depositum iman. Dalam ensiklik Humani Generis, Paus Pius XII menulis:
“Tuhan telah mempercayakan kepada Gereja tugas untuk menafsirkan Kitab Suci dan Tradisi Suci secara otentik, sehingga kebenaran ilahi dapat dijaga dari kesalahan dan disampaikan kepada semua generasi tanpa tercemar.” (Pius XII, Humani Generis, Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1950, no. 21)
Sejarawan Philip Hughes menyoroti bahaya tanpa otoritas ini:
“Protestantisme, dengan menolak Magisterium, telah menciptakan situasi di mana setiap orang menjadi paus bagi dirinya sendiri, menafsirkan Alkitab sesuai kehendaknya, sehingga menghasilkan perpecahan yang tak terhitung jumlahnya.” (Hughes, Philip, A History of the Church, vol. 3, London: Sheed & Ward, 1947, hlm. 289)
Tanpa Magisterium, “makelar iman” bebas mengubah kebenaran, menciptakan kekacauan di mana iman kehilangan sifat universal dan objektifnya.
6. Implikasi Teologis dan Praktis
Pendekatan Protestantisme yang mengutamakan penafsiran pribadi melemahkan kesatuan iman Kristen. Konsili Vatikan II, dalam Lumen Gentium, menegaskan peran Gereja:
“Gereja, dalam Kristus, adalah seperti sakramen, yaitu tanda dan alat untuk persatuan mesra dengan Allah dan untuk kesatuan seluruh umat manusia.” (Konferensi Waligereja Indonesia, Dokumen Konsili Vatikan II, Jakarta: KWI, 2003, hlm. 15, no. 1)
Jika iman dibiarkan di tangan “makelar” yang menawarkan versi-versi berbeda, visi kesatuan ini runtuh. Kebingungan muncul ketika doktrin inti – Trinitas, sakramen, keselamatan – diinterpretasikan secara kontradiktif. Gereja Katolik, dengan Magisteriumnya, menawarkan fondasi kokoh: iman yang dipandu Roh Kudus, terjaga dari subjektivisme.
7. Kesimpulan
Dari perspektif Katolik, pendekatan Protestantisme, khususnya “sola scriptura” dan penafsiran pribadi, membuka peluang bagi “makelar iman” – mereka yang merendahkan iman menjadi komoditas yang dibentuk sesuai kehendak manusia. Bukti sejarah menunjukkan ribuan denominasi yang terpecah, masing-masing mengklaim kebenaran subjektif. Dokumen seperti Dei Verbum, Katekismus Gereja Katolik, dan dekrit Konsili Trente menegaskan iman sebagai anugerah ilahi, dijaga oleh Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium. Tanpa ketiganya, iman menjadi barang di pasar rohani yang kacau, di
mana kebenaran diperjualbelikan. Gereja Katolik, berpijak pada warisan apostolik, menawarkan jalan pasti: iman yang utuh, universal, dan setia pada wahyu Kristus, bukan produk murahan dari pedagang rohani.3