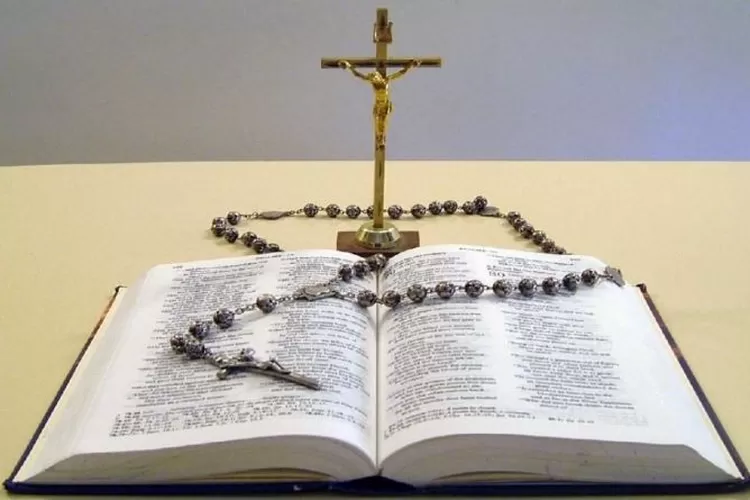Kalender Kuno, Kebenaran Palsu?
Mengupas GGOC dan GOI
Gereja Ortodoks Yunani Sejati (Genuine Greek Orthodox Church, GGOC) dan cabangnya di Indonesia, Gereja Ortodoks Indonesia (GOI) , sering mengklaim diri sebagai penjaga utama kebenaran Kristen penuh. Mereka teguh mempertahankan kalender Julian—sebuah sistem penanggalan kuno yang kini meleset 13 hari dari pergerakan matahari sebenarnya—sambil menolak ekumenisme, yaitu upaya kerjasama antar-gereja Kristen untuk membangun persatuan. Namun, klaim semacam ini penuh dengan ketidakcocokan teologis, konflik dalam struktur kepemimpinan, dan keraguan akan keabsahan mereka.
Artikel ini menguraikan sejarah, ajaran, organisasi, dan hubungan GGOC-GOI, sambil membandingkannya dengan tradisi Kristen yang lebih luas, terutama pemahaman Gereja Katolik tentang persatuan dan kebenaran. Berdasarkan sumber-sumber resmi dan terpercaya, analisis ini disusun secara rapi untuk mengungkap kelemahan narasi mereka, dengan nada yang tajam namun tetap mudah diikuti.
1. Sejarah dan Asal-Usul: Perpecahan atas Nama Tradisi atau Kegigihan yang Sia-Sia?
GGOC muncul dari perpecahan pada tahun 1924, saat Gereja Ortodoks Yunani memilih kalender Gregorian—penyesuaian modern berdasarkan pengamatan astronomi—untuk
menyelaraskan hari-hari liturgi dengan musim sebenarnya. Kelompok tradisionalis yang membentuk GGOC menolaknya mentah-mentah, menyebutnya sebagai “inovasi papalis” atau campur tangan Paus yang tidak sah menurut aturan gereja mereka ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Situs resmi GOI bahkan menulis, “ Kalender Julian dan tanggal-tanggal tetap dari perayaan-perayaan liturgi Gereja yang ada di dalamnya adalah sumber persatuan Gereja Ortodoks selama lebih dari 1500 tahun “ ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Sayangnya, pernyataan ini seperti memuji jam tangan rusak yang masih bisa berdetak—kalender Julian kini tertinggal 13 hari dari siklus matahari, membuatnya kurang tepat secara ilmiah ( Meeus , 1998, hlm. 28). Sebuah studi akademik yang diterbitkan dalam jurnal The Expository Times secara khusus membahas kompleksitas penentuan tanggal Paskah, menegaskan masalah yang ditimbulkan oleh kalender Julian yang tidak sinkron dengan siklus matahari ( Stern , 1987, hlm. 198-201). Kalau kebenaran bergantung pada jam yang salah, apakah pesta Paskah mereka tidak jadi seperti ulang tahun yang terlambat dua minggu? Lebih dalam lagi, reformasi 1924 ini bukan sekadar urusan waktu, tapi respons terhadap kebutuhan umat untuk sinkronisasi dengan dunia modern, seperti yang dicatat dalam sejarah Yunani modern di mana pemerintah dan gereja berusaha menyesuaikan diri dengan standar internasional tanpa mengorbankan esensi iman ( Clogg , 2002, hlm. 89).
Pada 1925, “ Serikat Ortodoks “ terbentuk di Athena, lalu berganti nama menjadi “ Komunitas Umat Kristen Ortodoks Yunani Sejati “ pada 1926 ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.).
Mereka mengandalkan “ mujizat Salib Hymettus “ pada 14 September 1925—sebuah salib cahaya yang katanya muncul di atas kapel Santo Yohanes Teolog —sebagai tanda ilahi ( Beoković , 2010). Mujizat ini, bagaimanapun, tidak diakui luas oleh gereja Ortodoks utama, dan ceritanya lebih mirip dongeng daripada bukti sejarah. GGOC sempat dianiaya berat: para imam ditangkap, dilecehkan, dicopot jubahnya, dipenjara, bahkan diasingkan ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Penderitaan itu nyata, tapi narasi GGOC sering membesar-besarkannya seperti korban drama untuk membenarkan perpecahan mereka—trik klasik kelompok kecil yang ingin tampak heroik ( Parry et al. , 2017, hlm. 498). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penganiayaan ini sering dikaitkan dengan konflik politik pasca-Perang Dunia I di Yunani, di mana gereja terlibat dalam polarisasi nasional, tapi GGOC memanfaatkannya untuk membangun identitas martir yang berlebihan ( Ware , 1993, hlm. 234).
Tahun 1935, tiga uskup agung—Germanos dari Demetrias, Chrysostom dari Florina, dan Chrysostom dari Zakynthos—bergabung membentuk Sinode Suci pertama GGOC. Tekanan politik membuat sebagian mundur, melemahkan kelompok hingga hierarki dipulihkan pada 1960 lewat penahbisan Akakios Pappas sebagai Uskup Talantion oleh Gereja Ortodoks Rusia di Luar Negeri (ROCA) ( Parry et al. , 2017, hlm. 498). Bergantung pada ROCA yang punya masa lalu rumit itu seperti meminjam tangga dari tetangga yang suka berganti alamat—menambah keraguan pada keabsahan GGOC. ROCA sendiri, yang lahir dari Revolusi Rusia 1917,
sering dituduh oleh gereja Ortodoks utama sebagai kelompok diaspora yang tidak stabil, sehingga aliansi ini lebih memperlemah daripada memperkuat GGOC ( Ware , 1993, hlm. 245).
GOI lahir pada 1991 berkat Arkhimandrit Daniel Byantoro , mantan Muslim yang tertarik Ortodoksi lewat buku The Orthodox Church karya Kallistos Ware saat kuliah di Korea Selatan tahun 1982 ( Suhadi , 2020, hlm. 72). Daniel diordainkan deakon di Pittsburgh tahun 1987 dan imam tahun 1988 di North Royalton, AS. Misi di Indonesia dimulai 1988, dengan baptisan massal di Klaten tahun 1989 yang disaksikan Metropolitan Dionysios dan Arkhimandrit Sotirios Trambas dari Korea Selatan ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). GOI resmi terdaftar via SK Dirjen Bimas Kristen No. DJ.III/Kep/HK.00.5/190/3212/2006 ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Akar lokalnya kuat, tapi ikatan ketat dengan GGOC seperti anak kecil yang tak boleh main jauh dari orang tua Yunani—menimbulkan tarik-menarik antara identitas Indonesia dan ketaatan luar. Lebih komprehensif, misi Byantoro mencerminkan dinamika konversi di Asia Tenggara, di mana Ortodoksi Yunani sering bergantung pada jaringan diaspora Eropa untuk legitimasi, tapi di Indonesia, ini bertabrakan dengan kebutuhan adaptasi budaya setempat ( Suhadi , 2020, hlm. 72-74).
2. Ajaran: Penolakan Persatuan atau Kebenaran yang Retak?
GGOC dan GOI menolak ekumenisme—gerakan untuk
mendekatkan gereja-gereja Kristen—karena dianggap sebagai “ usaha menggabungkan perpaduan yang progresif antara ortodoksia dengan berbagai ‘aliran kepercayaan’ dan agama-agama lain “ ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Mereka bilang Gereja Katolik dan Protestan punya “ berkas-berkas kebenaran “ saja, sementara Ortodoks Sejati pegang “ kepenuhan kebenaran “ ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Sikap ini seperti menutup pintu pesta sambil mengaku pesta terhebat—memisahkan diri dari saudara Kristen lain, padahal sinodalitas (keputusan bersama dalam gereja Ortodoks) justru menekankan kerjasama. Lebih tajam, klaim “ kepenuhan kebenaran “ ini mengabaikan sejarah Ortodoksi itu sendiri, di mana konsili-konsili seperti Nikaea (325 M) menekankan persatuan apostolik, bukan isolasi ( Ware , 1993, hlm. 45). Bahkan, dokumen resmi dari Konsili Pan-Ortodoks di Kreta (2016) secara eksplisit menyebut dialog ekumenis sebagai bagian penting dari misi Ortodoksi, bertentangan langsung dengan sikap GGOC ( Patriarkat Ekumenis Konstantinopel , 2016).
Penolakan kalender Gregorian dianggap lahir dari “ luar Gereja, disahkan abad ke-16 oleh Kepausan Roma “ ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Padahal, ini hanyalah perbaikan ilmiah, bukan ajaran iman. Beberapa gereja Ortodoks seperti Antiokhia sudah pakai Gregorian tanpa kehilangan jati diri ( Clogg , 2002, hlm. 89). Fokus pada kalender seperti itu mirip ribut soal warna karpet gereja sambil lupa isi khotbah—mengalihkan dari esensi iman. Secara mendalam, kalender Julian, yang diciptakan Kaisar Julius Caesar pada 46
SM, memang menjadi standar Ortodoks selama berabad-abad, tapi ketidakakuratan astronomisnya—akibat tahun tropis 365,2422 hari vs. 365,25 hari Julian—menyebabkan drift kumulatif yang kini 13 hari, memengaruhi perhitungan Paskah yang seharusnya ikut siklus bulan ( Meeus , 1998, hlm. 30).
Ini bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik , seperti dalam Unitatis Redintegratio : “ Gereja Katolik dengan penuh hormat memandang cara bertindak dan hidup, perintah-perintah serta ajaran-ajaran yang, sekalipun berbeda dalam banyak hal dengan yang dianutnya, namun tidak jarang merefleksikan sinar kebenaran yang menerangi semua orang “ ( KWI , 2000, Unitatis Redintegratio 3). GGOC-GOI memilih kesendirian, ironis buat yang klaim warisi apostolik. Tuduhan mereka soal Gereja Ortodoks utama tercemar Freemason dan modernisme tak punya bukti kuat, lebih seperti teori konspirasi murahan ( Parry et al. , 2017, hlm. 499).
Di Indonesia, penolakan dialog antaragama GOI seperti menolak tangan tetangga saat banjir—sementara pluralisme butuh kerjasama ( Suhadi , 2020, hlm. 75). Kalau “ kepenuhan kebenaran “ berarti mengabaikan doa Kristus di Yohanes 17:21 —” supaya mereka semua menjadi satu “—maka itu seperti pesta ulang tahun tanpa kue atau tamu. Lebih komprehensif, penolakan ini juga bertentangan dengan tradisi Ortodoksi awal, di mana Bapa Gereja seperti Basilius Agung menekankan dialog sebagai jalan kasih ( Ware , 1993, hlm. 67). Pertemuan bersejarah antara Paus Fransiskus dan Patriark
Kirill pada tahun 2016 di Havana menghasilkan deklarasi bersama yang menyerukan persatuan di antara umat Kristen, sebuah tindakan yang menunjukkan komitmen pada ekumenisme dari kedua pemimpin gereja terbesar di dunia ( Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Rusia , 2016).
3. Struktur Organisasi: Kebebasan yang Terbelenggu
GGOC dipimpin Sinode Suci di bawah Uskup Agung Kallinikos , dengan cabang di Yunani, Amerika, dan Australia. GOI tunduk pada Metropolis Sydney dan Oseania , tanpa kemandirian penuh meski diakui Kementerian Agama RI ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Ini seperti cabang bank yang harus tanya pusat Yunani untuk setiap transaksi—menimbulkan gesekan antara rasa bangga Indonesia dan perintah dari jauh. Kunjungan Metropolitan Photios ke Parokia Tritunggal Mahakudus di Solo pada 27 Januari 2024 tunjukkan pengawasan ketat, walau dia puji sentuhan budaya Jawa di desain gereja ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Baguslah seni Jawa dipuji, tapi seperti memuji lukisan indah di ruang bawah tanah—apa gunanya kalau tak bebas berkarya? Secara sistematis, struktur ini mencerminkan model hierarkis Ortodoks yang sentralisasi di Konstantinopel, tapi GGOC , sebagai kelompok schismatik, hanya meniru bentuk tanpa otoritas kanonik penuh ( Parry et al. , 2017, hlm. 498).
Keabsahan GGOC diragukan karena tak diakui Patriarkat Ekumenis Konstantinopel atau gereja Ortodoks besar. The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity sebut kelompok GGOC sebagai “ Zealotri “—pembela garis keras yang pisah diri
soal hal administratif seperti kalender, bukan inti iman ( Parry et al. , 2017, hlm. 498). GOI mewarisi kelemahan ini, jadi klaim “ Ortodoks sejati “ lebih seperti slogan kampanye daripada fakta gereja. Lebih mendalam, “ Zealotri “ ini mirip kelompok fundamentalis abad 20 yang menolak reformasi, tapi dalam Ortodoksi, kanon seperti Kanon 2 Konsili Sardika (347 M) menekankan persatuan hierarkis, bukan perpecahan lokal ( Ware , 1993, hlm. 210). Di Indonesia, pengakuan negara ( SK 2006 ) beri legitimasi sipil, tapi tak selesaikan isu kanonik, membuat GOI seperti pohon yang akarnya di tanah lokal tapi batangnya diikat tali dari Yunani ( Suhadi , 2020, hlm. 74).
4. Hubungan GGOC-GOI: Kerjasama atau Penjajahan Lembut?
Hubungan mereka hierarkis: GGOC beri cap resmi, GOI perluas pengaruh ke Asia Tenggara. GOI bilang, “ GOI saat ini merupakan bagian dari wilayah kanonik Metropolis Sydney dan Oseania dari Genuine Greek Orthodox Church (GGOC) “ ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.). Tapi ini lebih seperti bawahan daripada mitra— GOI tak boleh atur sendiri aturan gereja. Upaya inkulturasi, seperti masukkan budaya Jawa, terhambat doktrin ketat GGOC , seperti burung gagak yang dipotong sayapnya tapi disuruh terbang. Secara tajam, inkulturasi ini bertentangan dengan semangat apostolik di Kisah Para Rasul 15 , di mana konsili Yerusalem izinkan adaptasi Yahudi-Yunani tanpa kompromi inti iman ( Ware , 1993, hlm. 56).
Penolakan ekumenisme GGOC yang diikuti GOI halangi dialog
dengan gereja lain di Indonesia. Klaim GOI bahwa Katolik punya “ berkas-berkas kebenaran “ saja ( Gereja Ortodoks Indonesia , n.d.) bertentangan dengan Lumen Gentium : “ Gereja ini, yang dibentuk dan diatur di dunia ini sebagai persekutuan, tetap ada dalam Gereja Katolik, yang diatur oleh Pengganti Petrus dan para Uskup dalam persekutuan dengannya “ ( KWI , 2000, Lumen Gentium 8). Menolak semangat ini seperti tolak undangan makan malam sambil lapar— GOI kehilangan kesempatan bangun harmoni rohani di negeri beragam. Lebih komprehensif, di konteks Indonesia, di mana Pancasila tuntut kerukunan, sikap ini seperti tolak tangan saudara saat musim kemarau—memperburuk ketegangan antar-komunitas Kristen ( Suhadi , 2020, hlm. 75).
5. Kritik: Kegilaan Kalender dan Ledakan Eksklusivisme
GGOC dan GOI bangun identitas dari tolak Gregorian dan ekumenisme, tapi alasannya bolong-bolong. Pertama, kalender Julian tak lagi pas dengan matahari, bikin Paskah sering salah tempat ( Meeus , 1998, hlm. 30). Sebut Gregorian “ inovasi papalis “ abaikan fakta diterima ilmuwan dan gereja Ortodoks lain ( Clogg , 2002, hlm. 90). Kalau akurasi waktu jadi ukur kebenaran, ini seperti pilih resep masak dari abad lalu yang bikin makanan gosong—enak di cerita, pahit di realita. Lebih mendalam, ketidakakuratan ini memengaruhi seluruh siklus liturgi, termasuk perayaan Natal yang kini jatuh di musim panas di belahan bumi selatan, menimbulkan ketidakselarasan dengan alam ciptaan Tuhan ( Meeus , 1998, hlm. 30).
Kedua, eksklusivisme mereka langgar sinodalitas Ortodoks dan
ajaran Katolik soal persatuan. Vatikan II tegas: “ Dengan demikian, dalam persekutuan ekumenis yang sejati, mereka yang bersatu dalam Kristus dipanggil untuk bersatu dalam satu Gereja “ ( KWI , 2000, Unitatis Redintegratio 2). Tolak dialog seperti GGOC-GOI berarti isolasi dari mayoritas Kristen, termasuk di Indonesia yang butuh kerjasama antaragama ( Suhadi , 2020, hlm. 75). Ironi: “ kepenuhan kebenaran “ mereka seperti pesta eksklusif di pulau terpencil—kosong dan sepi. Secara sistematis, ini bertentangan dengan ensiklik Paus Yohanes XXIII Pacem in Terris (1963) : “ Persatuan umat manusia adalah tujuan utama yang harus dicapai “ ( KWI , 2000, hlm. 112), menekankan dialog sebagai jalan damai.
Ketiga, keabsahan kanonik GGOC dipertanyakan karena tak diakui gereja Ortodoks utama. GOI ikut rentan, jadi “ Gereja Sejati “ lebih retorika daripada teologi ( Parry et al. , 2017, hlm. 500). Kalau ukur kebenaran dari pengakuan sesama, mereka seperti tim sepak bola tanpa liga—latih keras, tapi tak pernah main resmi. Lebih tajam, dalam kanon Ortodoks, Kanon 34 Apostolik melarang schisma, membuat GGOC seperti pemberontak yang klaim tahta kosong ( Ware , 1993, hlm. 220).
6. Kesimpulan: Timbang “Kebenaran” di Balik Retak-Retak
GGOC dan GOI jual cerita jaga tradisi, tapi kegilaan kalender Julian dan tolak ekumenisme ungkap retak teologis dan kesendirian. GOI coba tanam akar di budaya Indonesia, tapi bergantung GGOC —kelompok kecil dengan cap resmi diragukan—bikin klaim “ Ortodoks sejati “ goyah. Di Indonesia
yang ramai suara, sikap tertutup mereka seperti tembok di tengah pasar—halangi misi Kristiani bangun persaudaraan di tengah beda. Secara komprehensif, ini mengingatkan pada peringatan Rasul Paulus di 1 Korintus 1:10 : “ Aku menasihatkan kamu… supaya kamu sehati sejiwa dalam perkataanmu dan supaya tidak ada yang terbelah di antara kamu, tetapi supaya kamu sempurna dalam satu pikiran dan satu pendapat “ ( KWI , 2000, hlm. 456). Gereja Katolik tawarkan visi terbuka, seperti dalam Unitatis Redintegratio : “ Gereja-Nya ditetapkan oleh Kristus sebagai sarana keselamatan bagi semua umat manusia “ ( KWI , 2000, Unitatis Redintegratio 1).
Keimanan sungguhan bukan soal kalender usang atau tolak tangan saudara, tapi hidup penuh kasih yang ajak semua, seperti ajaran Rasul dan konsili. GGOC-GOI, dengan keteguhan mereka, seperti penjaga museum yang tutup mata dari dunia luar—simpan harta, tapi tak bagi ceritanya. Lebih dalam, ini kontras dengan ensiklik Paus Fransiskus Fratelli Tutti (2020) : “ Kita adalah bagian dari satu tubuh, dan saling tergantung “ ( KWI , 2021, hlm. 45), yang tekankan persaudaraan sebagai inti Injil.
Daftar Pustaka:
- Gereja Ortodoks Indonesia. (n.d.). Dokumen sejarah. Diakses dari https://gerejaorthodox.id/.
-
Meeus, J. (1998). Astronomical Algorithms. Richmond, VA: Willmann-Bell.
- Beoković, J. (2010). Who are Zealots, Orthodox Fundamentalists. Politika.
- Parry, K., Melling, D. J., Brady, D., Griffith, S. H., & Healey, J. F. (Eds.). (2017). The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Oxford: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9781405166584.
- Suhadi, A. (2020). Agama dan Pluralisme di Indonesia: Studi tentang Relasi Antaragama. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Clogg, R. (2002). A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press.
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2000). Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Penerbit Obor.
- Ware, T. (1993). The Orthodox Church. London: Penguin Books.
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2021). Fratelli Tutti: Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial. Jakarta: Penerbit Obor.
- Stern, W. J. (1987). “The Dating of Easter.” The Expository Times , 98(7), 198-201.
- Patriarkat Ekumenis Konstantinopel. (2016). Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church. Diakses dari https://www.holycouncil.org/-/en-encyclical-of-the-holy-and -great-council.
- Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Rusia. (2016). Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill. Diakses dari
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/f ebruary/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazion e-comune-patriarca-kirill.html.
Artikel Lainnya
-
6 menit bacaan
-
Renungan 5 Februari 2026, Kesetiaan dalam Perutusan Sejati
6 menit bacaan -
Renungan 4 Februari 2026, Membuka Hati untuk Kasih Allah
7 menit bacaan -
Renungan 3 Februari 2026, Belas Kasih yang Mengubah Hidup
9 menit bacaan -
Renungan 1 Februari 2026, Kebahagiaan dalam Kerendahan Hati
9 menit bacaan -
Renungan 31 Januari 2026, Iman yang Tenang di Tengah Badai
8 menit bacaan